Demokrasi seutuhnya yang diinginkan rakyat semenjak reformasi 10 tahun silam, pada akhirnya mencapai puncak ketika masyarakat Indonesia melangsungkan hajatan pemilihan umum (presiden dan legislatif) 2004 lalu. Dalam pemilihan umum (Pemilu) 2004 tersebut, tonggak sejarah ditancapkan dengan digelarnya pemilihan langsung (langsung memilih calon) wakil rakyat (legislatif) dan Presiden (beserta wakilnya).
Namun berlangsungnya proses demokrasi tersebut tidaklah diikuti praktek politik yang arif dan bijak (sesuai yang diharapkan masyarakat) oleh sebagian besar elite politik yang terpilih dalam pemilu. Sehingga janji-janji untuk membawa perubahan disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pun terhambat bahkan jalan ditempat. Hal inilah yang kemudian memancing reaksi ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap jalannya pemerintahan.
Sikap tidak percaya itu salah satunya dapat terlihat dengan banyaknya demontrasi yang dilakukan masyarakat terhadap Pemerintah. Ketidakpercayaan tersebut diperkirakan akan menimbulkan sikap apatis terhadap proses demokrasi dalam Pemilu yang digelar tahun 2009 mendatang. Sehingga diprediksi masyarakat yang yang tidak menggunakan hak suara (golongan putih – golput) akan semakin meningkat.
Potensi pemilih golput pada Pemilu 2009 mendatang diperkirakan akan membengkak lebih dari 40%. Indikasi tersebut bisa disaksikan pada data pilkada (pemilihan kepala daerah) Jawa Tengah (Jateng) yang golputnya mencapai 44%.
Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa fenomena golput lahir akibat ketidakpercayaan akan kinerja para legislatif maupun eksekutif, yang kebanyakan tidak sesuai dengan janji yang diutarakan pada saat kampanye. Sikap apatis dari masyarakat itu tentu akan menjadi sebuah masalah besar dinegeri ini, karena bagaimanapun pemilihan umum adalah jalan menuju sebuah kehidupan bernegara, setidaknya lima tahun kedepannya.
Agung Laksono (Wakil Ketua DPR RI) berkomentar dalam sebuah portal berita, masyarakat bisa saja kecewa terhadap anggota DPR atau politisi, namun DPR merupakan lembaga negara yang perlu diisi. Menanggapi kemungkinan masyarakat tidak memilih dalam pemilu (golput), Sekjen PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) versi MLB Parung Yenny Wahid dalam sebuah kesempatan juga mengungkapkan, sikap apatis masyarakat terhadap politisi di DPR memang dapat muncul. Oleh karena itu, dalam Pemilu 2009 nanti, masyarakat perlu memilih anggota DPR yang memiliki integritas dan berkualitas.
Nah, satu hal yang harus digaris bawahi dari pernyataan putri sulung Gus Dur (Abdurrahman Wahid) tersebut, yaitu masyarakat harus tetap mengunakan hak pilih dengan memilih anggota DPR yang memiliki integritas dan berkualitas. Namun bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui integritas dan kualitas calon wakilnya di parlemen ? Jawabnya, harus ada pembelajaran politik untuk masyarakat. Dan fungsi inilah yang seharusnya diemban oleh pers sebagai alat kontrol dalam kehidupan bernegara.
Sikap apatis dan hilangnya kepercayaan terhadap calon legislatif dan eksekutif sebenarnya banyak disebabkan oleh masyarakat sendiri. Banyak masyarakat yang terkesima dengan figur yang dipilih karena berhasilnya para tim sukses membangun “brand” para figur. Figur para calon sengaja dibangun sedemikian rupa bahkan “menghalalkan” segala cara untuk mendulang suara publik. Diantaranya dengan praktek black campaign, yaitu politik uang money politic. Disinilah pembelajaran politik tersebut perlu dilakukan.
Ditengah kebebasan demokrasi seperti saat ini siapapun berhak maju pencalonan, baik sebagai kepala daerah, legislatif, maupun menjadi kepala negara (asal tidak menyalahi undang-undang tentunya). Disaat mendekati hari-hari menjelang kampanye, semua calon yang maju berlomba membangun “personal brand” masing-masing. Publikasi dan promosi yang terang-terang maupun samara-samar dilakukan dimana-mana. Salah satunya juga menggunakan mass media.
Disinilah peran pers sangat menentukan. Seharusnya sebagai fungsi kontrol sosial, pers melalui medianya dapat menghadirkan sebuah paparan dan ulasan mengenai sosok-sosok sang kandidat, termasuk juga track record selama yang bersangkutan berkarier baik dalam politik maupun bisnis.
Kenyataan lain yang terjadi saat ini, pers melalui medianya kebanyakan lebih memanfaatkan momen demokrasi langsung (pemilihan langsung) untuk tujuan bisnis semata, bukan menghadirkan sebuah pembelajaran untuk masyarakat. Iklan-iklan politik tiap hari menjejali halaman koran, portal berita, spot televisi maupun radio. Tidak jarang pula pesan kampanye dihias dalam bingkai advertorial yang menyerupai berita. Dari sini jelas, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan kelas C kebawah akan menelan begitu saja pesan politik yang memuat janji-janji manis tersebut, karena dikiranya sebuah berita.
Bahkan yang lebih ekstrem, sebuah media di Surabaya sempat memuat iklan politik full di halaman A1 (halaman paling depan). Kalau kondisinya sudah seperti ini, jangan salahkan jika masyarakat gampang teriming-iming dengan janji politik serta money politik.
Era kebebasan juga dimanfaatkan oleh para kandidat (yang bertarung dalam pemilihan) untuk menggunakan berbagai cara dalam meyakinkan calon pemilih. Salah satu yang banyak dan sering kali digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan emosioanal pada masyarakat. Itulah kadang yang membuat masyarakat terlena, sehingga integritas dan kualitas calon tidak lagi menjadi pertimbangan para pemilih (masyarakat).
Ambil contoh seorang calon gubernur Jawa Timur. Dalam beberapa komunikasi politiknya di Surabaya calon tersebut acap kali mencitrakan diri sebagai tokoh dibalik nama besar dan prestasi klub sepak bola kebanggaan warga Surabaya, Persebaya.
Saya berani bertaruh, masyarakat di kelas sosial C kebawah terlebih yang mempunyai ikatan emosional dengan Persebaya (salah satunya mungkin kelompok Suporter Surabaya, Bonek) pasti akan banyak yang memberikan dukungannya kepada calon gubernur tersebut. Padahal jelas, seharusnya masyarakat lebih memikirkan kepentingan yang lebih luas. Sebab seorang calon gubernur Jawa Timur haruslah sosok yang mampu menanggani berbagai permasalahan provinsi ini, salah satu yang terberat mungkin kasus Lumpur Panas Sidoarjo.
So, keberhasilan seseorang memimpin sebuah klub sepak bola belum tentu ada korelasinya dengan keberhasilan menyelesaikan permasalahan propinsi kan ? Disinilah mengapa dari awal perlunya ada sebuah pembelajaran politik untuk masyarakat.
Kalaupun nantinya sudah ada pembelajaran, maka sudah saatnya lah hati nurani masyarakat yang harus berbicara dalam bilik suara. Bukan lagi memilih berdasarkan kedekekatan emosional, kaos politik, sumbangan sembako, ataupun bentuk money politic lainnya. Cara berpikir kritislah yang menentukan perjalanan demokrasi bangsa ini, bukan dengan sikap apatis !
* Tulisan untuk tugas kuliah Sistem Pers Indonesia (Menyikapi apatis masyarakat terhadap Pemerintah).
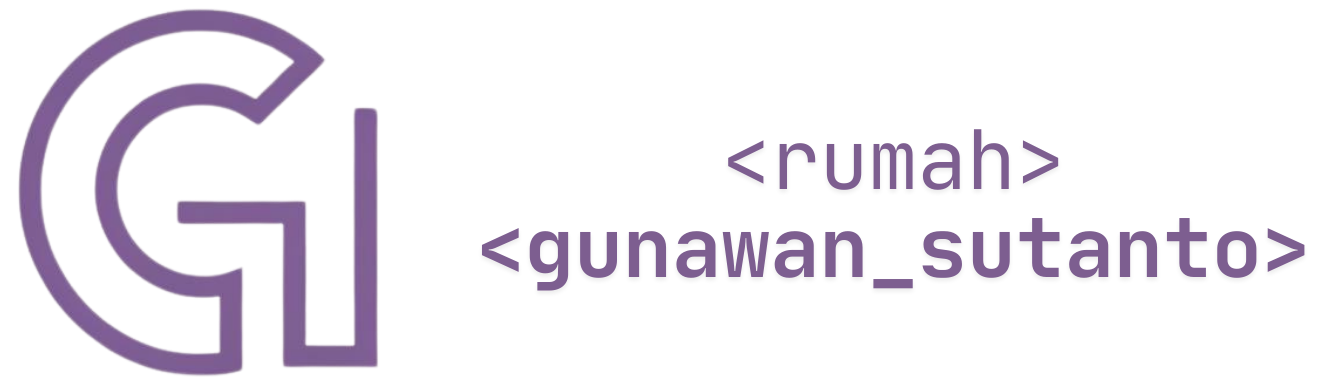

0 comments on “Kritis Tanpa Apatis*”Add yours →