SEBAGAI warga Surabaya sekaligus pendukung setia Persebaya, saya miris melihat dan membaca berita media massa seputar tragedi Bonekmania yang road to Bandung. Lagi-lagi, militansi warga Surabaya yang berlabel Bondo Nekat (Bonek) itu harus dibayar mahal. Untuk bisa mendukung Green Force bertanding, nyawa mereka jadi taruhan.
Lepas dari kejadian itu apakah Bonek bersalah atau tidak, saya melihat kini fenomena militansi suporter Surabaya memang mulai kebablasan. Namun, hal tersebut tidak hadir tanpa sebab. Layaknya kehidupan keluarga, Bonek kini bagaikan anak salah asuhan. Gak duwe emak, diumbar karo bapake.
Saya bilang begitu karena saya pernah melihat masa di mana suporter Surabaya setidaknya bisa lebih baik dari sekarang. Saat-saat ketika suporter terkoordinasi dan mendapat pendampingan dengan baik.
Catatan ini saya buat berdasar pengalaman pribadi. Plus, sebelum menulis, saya sempat berdiskusi dengan mantan wartawan Jawa Pos. Dia dulu sempat beberapa kali kebagian tugas menjadi koordinator suporter saat Persebaya masih dikomandani Dahlan Iskan. Dari situ, saya bisa membandingkannya.
Peristiwa yang masih lekat di ingatan wartawan itu adalah ketika Persebaya tret tet tet (sebutan untuk berangkat mendampingi Persebaya tandang) ke Senayan, 1989. Kala itu, Persebaya berhasil ke final dan bertanding di Jakarta menghadapi Persija.
Dia bercerita, pada zaman itu, militansi arek Suroboyo tak berbeda dari sekarang. Tawuran tetap iya, ambil makan tanpa bayar ada, termasuk olok-olokan antarsuporter juga sama. Hanya, militansi tersebut tak berbuah petaka seperti sekarang. Sebab, kala itu para suporter terkoordinasi dengan baik.
Menurut dia, dulu untuk memberangkatkan suporter ke Jakarta, Dahlan Iskan memanfaatkan jaringan agen dan penyalur Jawa Pos. Di tempat-tempat tersebut, para suporter yang ingin ke Jakarta bisa membeli tiket. Tiket yang dimaksud bukan sekadar tiket menonton ke stadion, tapi paket tiket perjalanan ke Jakarta. Mereka yang mendaftar, selain mendapatkan tiket masuk stadion, memperoleh jatah kaus, syal, serta akomodasi perjalanan (bus pulang pergi dan makan dua kali).
Kala itu ada 36 bus yang diberangkatkan. Dari Surabaya berangkat malam, dapat makan di perjalanan, dan paginya sampai Jakarta. Di setiap bus, terdapat seorang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab yang dipercaya memegang uang dan tiket. Sesampai di ibu kota, para suporter sudah memegang tiket masuk ke stadion. Tidak hanya keberangkatan yang dikoordinasi, tapi juga kepulangan suporter. Balik dengan bus dan dapat jatah makan di perjalanan.
Antusiasme suporter yang ikut dalam rombongan tersebut jauh lebih banyak daripada mereka yang berangkat sendiri-sendiri. Itu zaman dulu. Coba bedakan dengan sekarang, kondisinya begitu timpang. Bonek-Bonek seperti gak kopenan.
Jangankan mendapat fasilitas dan pendampingan saat tandang, menonton pertandingan di kandang pun tak ada bedanya. Saya merasakan ketimpangan itu ketika harus menonton pertandingan big match antara Persebaya melawan Arema Indonesia di Gelora 10 Nopember, Sabtu lalu.
Waktu itu, jelas-jelas Saleh Ismail Mukadar, ketua umum Persebaya sekaligus calon wali kota, menulis pesan di Facebook-nya bahwa penjualan tiket dibuka pukul 11.00. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Panpel mengumumkan melalui pengeras suara bahwa tiket habis sejak pagi. Semua ludes, baik kelas ekonomi, utama, maupun VIP.
Ironisnya, tiket habis di loket, tapi bertebaran di calo-calo yang bergentayangan di sekitar stadion. Tiket tersebut dijual di luar batas kemampuan kebanyakan Bonekmania. Tiket ekonomi yang semula berlabel Rp 20 ribu, di tangan calo menjadi paling murah Rp 50 ribu.
Karcis utama yang aslinya Rp 50 ribu dijual terendah Rp 75 ribu. Yang lebih gila, tiket VIP dijual Rp 150 ribu, harga normalnya Rp 100 ribu. Itulah yang menurut penilaian saya sumber militansi Bonek yang kebablasan tersebut muncul.
Mungkin bagi Bonek yang berduit, harga tiket berapa pun tak masalah, asal bisa mendukung langsung Green Force di lapangan. Tapi, bagi mereka yang harus nyelengi, ngutang, atau ngamen, berbeda rasanya. Mereka pasti melongo dan emosional. Sebab, uang yang didapat dengan susah itu tak berarti gara-gara harga tiket di tangan calo berlipat.
Jadi, jangan salahkan kalau para Bonekmania di sana kehilangan kesabaran. Anarkisme mereka timbul karena pengorbanan tak sesuai harapan. Di sinilah pengurus Persebaya tidak berhasil atau mungkin sengaja membiarkan kondisi semacam itu terjadi. Sebab, apakah kira-kira petugas loket tidak mengenali wajah calo tiket yang ”koen maneh koen maneh”?
Bagaimanapun, mayoritas Bonekmania merupakan warga Surabaya. Militansi mereka tidak perlu dikebiri, tapi dikoordinasi supaya bisa membanggakan. Itu yang penting.
Salah satu upaya mendesak yang harus dilakukan mungkin soal pengorganisasian tiket. Kalau dulu tiket disebar di agen dan penyalur Jawa Pos, apakah tidak mungkin sekarang dikoordinasi per kecamatan atau kelurahan di Surabaya?
Sebab, jika tidak dicarikan solusi, dikhawatirkan militansi yang kebablasan itu akan terbawa sampai Persebaya memanfaatkan Gelora Bung Tomo, Surabaya Sport Center, sebagai tempat bertanding. Bisa dibayangkan betapa ruginya kalau infrastruktur di kompleks olahraga tersebut ikut jadi sasaran emosi suporter hanya gara-gara hal sepele.
—
Gunawan Sutanto, Wartawan Jawa Pos
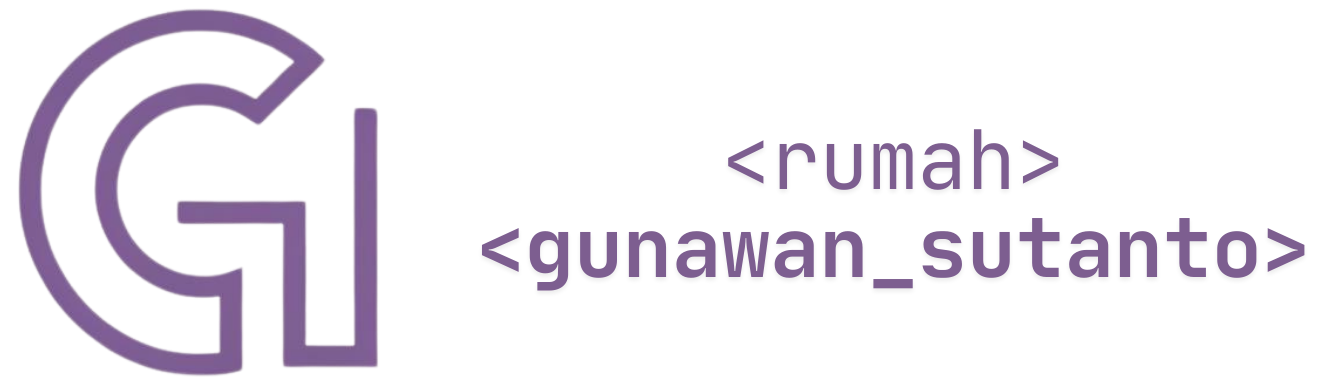

0 comments on “Bonek; Gak Duwe Emak, Diumbar Karo Bapake”Add yours →